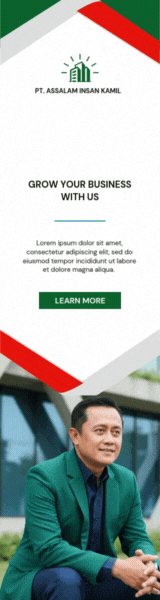Oleh: Ansyori Ali Akbar (Jurnalis)
Jum’at 21 novemeber 2025 Tepi Sungai Way Kiri, Lampung
Susana yang hening dan sepi tangan ku menulis cepat, tulisan agak bergelombang karena angin sepoi-sepoi menyentuh kertas, seperti ombak yang pelan melukis pasir di pantai.Mataku panas, karena tadi pagi aku melihat sepasang sepatu aus yang mirip dengan sepatu Rio dulu dan teringat dengan semua dengan apa yang telah di lalui. Tanpa sadar, air mata sudah menetes di kertas.
Aku adalah nasikin, orang yang jalan-jalan tanpa rencana, tanpa jadwal, cuma bawa buku catatan dan sepasang sepatu yang udah aus. Dunia efisiensi melihatku seperti barang rusak: terlalu lambat, terlalu acak, terlalu “tidak bermanfaat”.
Tapi aku mau tulis satu hal yang jujur di jurnal perjalanan ini: kepedihanku itu nyata banget, tapi kangenku pada jalan sebagai rumah itu – serta kehadiran Tuhan yang selalu ada di hati kayak bintang yang menerangi malam yang paling gelap – lebih dalam dari apa pun yang dunia efisiensi bisa berikan.

Pendapatanku bergantung pada tulisan yang aku buat tentang jalanan Indonesia, warga, dan hal-hal yang dunia bilang “tidak penting”. Dunia ngomong: “Tulis cepat, tulis banyak, itu yang bikin uang.” Tapi aku ? Aku mau tulis apa yang aku rasakan, dan itu butuh waktu, kayak bunga yang butuh hari-hari buat mekar, bahkan kalau harus menanti hujan yang lama.
Malam ini, aku tidak tidur di warung seperti yang rencanaku, tapi ke masjid tua yang ada di tepi jalan. Lantai batu dingin menyentuh kulitku, tapi suasana tenang banget – kayak kamar tidur yang sudah menunggu lama, meskipun sudah kosong. Aku duduk di sudut masjid, perut kosong kayak ladang yang kering sepanjang musim, tapi tiba-tiba ada rasa tenang yang menyelimuti.
Sambil menutup mata, aku merasakan Tuhan yang lembut memelukku dari balik dada – dan seolah-olah dia berbisik lembut di telingaku: “Jangan takut, aku ada di sini – kayak naungan pohon di tengah panas hari yang bikin orang pingsan.”

Baru beberapa menit kemudian, pedagang Pak Min datang ke masjid dengan segelas teh tawar yang hangat dan sepotong roti yang masih panas. Dia bilang: “Kamu kelihatan lelah, nak. Ini buatmu –Ia berkata dari hati. Aku juga pernah ada di posisi mu dulu, nggak ada uang, nggak ada tempat cuma ada harapan” dan Tuhan.
Aku ngangguk, mata panas sampai air mata menetes tanpa terasa, karena aku tahu, kebaikan warga lokal itu bukan cuma dari Pak Min, tapi juga tanda bahwa aku tidak sendirian, kayak burung yang selalu punya teman di langit meskipun terbang sendirian. Pendapatanku yang seharusnya datang hari ini? “Sedang dalam proses verifikasi efisien.” Efisiensi yang bikin aku lapar, tapi tidak bikin aku lupa kehadiran yang selalu ada, dan betapa pahitnya merasa diabaikan oleh dunia yang cuma mau cepet.
Dan tahu apa yang paling menyakitkan ? Ketika sahabatmu yang dulu sama jalannya juga mulai mengikuti omongan dunia – kayak kapal yang dulu sama arah, tapi sekarang berbelok ke pelabuhan yang berbeda, dan lupa bahwa kita pernah berlayar bersama di laut yang ganas.
Tadi pagi, Rio telepon suaranya pelan tapi tegas, kayak pisau yang lembut tapi bisa menusuk dalam: “Bro, kapan kamu mau berhenti main-main jalan-jalan? Cari kerja yang tetap lah, biar hidupmu efisien, tidak kacau. Orang lain udah punya rumah, punya mobil – kamu? Cuma punya sepatu aus dan buku catatan.”
Rio , sahabatku yang dulu selalu ikut aku jalan-jalan tanpa rencana di Indonesia, yang pernah sama aku tidur di bale desa dan berdoa di tepi sungai – kayak dua batang padi yang tumbuh berdampingan, saling menopang saat angin kencang. Aku ingat dia pernah bilang: “Kita akan selalu jalan bareng, bro, sampai kita temukan apa yang kita cari.”
Aku diam sejenak, mata panas kayak air matang yang mau tumpah. “Rio, ini bukan main-main. Ini cara aku hidup ,cara aku merasa bahwa aku benar-benar ada di dunia ini, sambil merasakan Tuhan yang memelukku dan berbisik: ‘Aku akan arahkan langkahmu, jangan ragu’ kayak kompas yang tidak pernah salah arah.”
Dia menghela napas, suara penuh keputusasaan: “Hidup yang apa? Kalau tidak ada uang, tidak ada masa depan itu bukan hidup, itu cuma bertahan. Aku udah lelah nunggu kamu, bro. Aku mau hidup yang stabil dan efisien.”
Suaranya seperti petir yang menyambar hati – membelah kedalaman yang dulu penuh kehangatan, sampai hanyut tinggal lubang kosong. Aku ingat tahun lalu, kita berdua jalan-jalan ke pantai Lampung, ngobrol sampai pagi dan melihat matahari terbit bersama, kayak melihat awal dari semua hal yang indah, yang kita pikirkan akan selalu ada. Tapi sekarang, dia sudah bekerja di perusahaan besar, terjebak dalam jadwal yang ketat dan omongan tentang “efisiensi” setiap hari kayak burung yang terkurung di sangkar yang indah tapi tidak bebas, dan malah lupa bagaimana caranya terbang.
Pas telepon terputus, aku duduk di tepi jalan mata kuat coba menahan, tapi air mata tetap menetes tanpa terasa, jatuh ke jalan tanah yang licin, hilang tanpa jejak seperti semua kehangatan persahabatan yang dulu ada.
Hari ini, aku tersesat di hutan Lampung. Hp habis batre, dan hujan turun deras kayak air mata dunia yang marah karena semua yang salah. Aku duduk di bawah pohon beringin, baju basah kedinginan sampai menggigil, dan berpikir: “Apakah aku beneran bodoh yang tidak mau menerima realitas dunia? Apakah Rio bener, aku cuma bertahan bukan hidup?”
Tapi tiba-tiba, ada seekor burung cucak ijo hinggap di cabang pohon di depanku. Dia tidak peduli hujan, tidak peduli kalau aku tersesat dia cuma bernyanyi dengan suaranya yang kecil tapi jernih kayak musik yang dibuat khusus buatku, untuk ngasih tahu bahwa aku masih berharga. Dan pada saat itu, semua keraguan aku hilang kayak kabut yang sirna ketika matahari terbit, menunjukkan bahwa jalan masih ada.
Sambil mendengar nyanyian burung itu, aku merasakan Tuhan yang lembut memelukku di tengah kegelapan hutan dan berbisik: “Ini juga bagian dari jalanmu – kayak batu yang jadi pijakan di jalan licin yang bikin orang terjatuh berkali-kali.”
Aku mulai bernyanyi juga – suaraku kaku dan tidak bagus, tapi itu tidak masalah. Di tengah hutan yang sunyi dan hujan yang deras, aku dan burung itu bikin irama sendiri – irama yang tidak efisien, tidak teratur, tapi penuh makna dan kehadiran yang tak terlihat – kayak aliran sungai yang lambat tapi selalu menemukan jalan ke laut, meskipun harus melewati bebatuan yang banyak. Tanpa sadar, air mata lagi-lagi menetes tanpa terasa – tapi kali ini karena rasa lega, karena tahu bahwa meskipun sendirian, aku tidak sendirian.
Ada banyak kepedihan di jalan: hujan yang basahi semua baju, jalan yang licin bikin aku terjatuh berkali-kali, orang yang menatap aneh dan bilang “Kenapa kamu tidak kerja seperti orang lain? Kamu bodoh ya?”. Tapi ada satu kepedihan yang paling dalam – yang bikin aku ingat selamanya: kulit lintah yang menempel di kakiku saat aku menyebrang Sungai Way Kiri.
Mulai itu menyakitkan, gatal banget, bikin aku ingin melemparkannya ke jauh-jauh – kayak duri yang masuk di jari dan tidak mau keluar. Aku coba cabut, tapi dia semakin erat, menyedot darahku sedikit demi sedikit kayak dunia efisiensi yang menyedot kebahagiaan dan kebebasan orang. Sampai akhirnya, aku berhenti dan biarkan dia menempel sana selama beberapa jam.
Sambil menanti dia lepas, aku berdoa pelan – dan merasakan Tuhan yang memelukku erat, berbisik: “Terima ini sebagai bagian dari perjalananmu aku ada di sini” kayak garam yang bikin makanan lebih enak, tapi rasanya pahit saat pertama kali dimakan.
Ketika dia lepas sendiri, tinggalkan bekas yang merah dan menyakitkan – tapi juga rasa ketenangan yang aneh – seolah semua kesedihan itu hilang, diganti dengan rasa bahwa aku telah merasakan sesuatu yang sesungguhnya. Itu seperti hidupku. Dunia efisiensi mencoba “cabut” aku dari cara hidup dengan hati yang “tidak efisien” – dengan omongan yang menyakitkan, dengan perlakuan yang tidak adil – kayak angin kencang yang coba tumbangkan pohon yang berdiri tegak. Tapi setiap kepedihan itu malah membuatku lebih kuat – dan lebih rindu pada jalan serta yang ada di dalam hati. Kepedihan itu bukan lubang yang harus diisi, tapi lukah yang membuat kita ingat: kita masih bisa merasakan – kayak bunga yang tumbuh dari lubang batu, menunjukkan bahwa harapan masih ada meskipun di tempat yang paling tidak mungkin.
Di kota kecil di Lampung, aku berhenti di warung nasi bakar yang cuma ada satu bangku – kayak rumah kecil yang menyambut dengan hangat meskipun aku orang asing. Pedagangnya adalah cewek seumuran aku, namanya Siti, yang selalu tersenyum meskipun ramai – kayak bunga melati yang selalu wangi meskipun di tengah jalan raya yang kotor. Aku beli nasi bakar sebesar lima ribu, tapi dompetku cuma ada empat ribu. “Maaf, mbak – cuma ada empat ribu,” Ujarku malu.
Dia tersenyum, “Gapapa, nak. Ini cuma nasi bakar doang. Tambahin sambal extra ya, biar lebih enak.” Dia tambahin sambal dan satu potong tempe lagi tanpa minta uang.
“Kamu kelihatan lagi jalan-jalan ya ?” dia tanya, sambil membungkus nasi.
“Apa ya, bagaimana kamu tahu ?”
“Karena matamu terlihat lelah tapi ceria kayak orang yang selalu mencari sesuatu yang baru, sesuatu yang dunia lain lewati, dan kayak orang yang punya sesuatu yang membuat hati tenang kayak air sungai yang jernih di tengah hutan yang gelap. Kamu ingat nggak, tahun lalu ada orang yang sama kayak kamu nasikin jalan-jalan sendirian, bawa sepatu aus. Dia bilang, ‘jalan itu adalah rumah dan rumah itu selalu ada di hati’.”
Kita ngobrol sampai malam dia menceritakan impiannya buat buka warung yang lebih besar, aku menceritakan tentang jalanan yang aku lewati dan Rio yang sudah berpisah.
Tidak ada omongan tentang efisiensi, tidak ada omongan tentang uang cuma cerita, senyum, dan rasa damai yang sama kayak langit yang cerah setelah hujan yang deras. Pas aku mau pergi, dia kasih satu bungkus nasi bakar lagi.
“Buat jalan, ya. Jangan lupa makan sehat itu lebih penting dari segalanya, dan hati yang tenang itu paling berharga – kayak matahari yang menyinari semua hal yang terluka.”
Aku berjalan keluar dari warung, membuka bungkus nasi bakar dan di dalamnya ada sepuluh ribu rupiah. Tangan aku gemetar, air mata menetes tanpa terasa jatuh ke bungkus kertas yang basah, mencampur dengan bau nasi bakar yang harum. Itu yang dunia efisiensi tidak bisa berikan: kebaikan yang tiba-tiba, cerita yang menyentuh, kenangan yang harganya lebih dari semua uang di dunia, dan kehadiran Tuhan yang selalu memelukku meskipun malam yang paling gelap.
Dunia akan terus berputar dengan kecepatan yang semakin tinggi – mengejar uang, mengejar prestasi, mengejar tujuan yang selalu jauh – kayak roda yang tidak pernah berhenti, sampai lupa apa yang ada di sekitarnya, sampai lupa bagaimana caranya merasakan.
Tapi aku? Aku akan terus menjadi nasikin di Indonesia. Aku akan terus berhenti buat lihat bunga di tepi jalan, ngobrol sama warga lokal yang menceritakan cerita nenek moyang, tidur di bale desa atau masjid tua sambil melihat bintang-bintang yang banyak banget kayak orang yang berhenti buat menghitung bintang di tengah kegelapan, karena setiap bintang adalah harapan.
Dan aku akan selalu berhenti untuk merasakan Tuhan yang memelukku dan berbisik di telingaku – yang menjadi kompas dan tempat berteduh di semua jalan kayak payung yang melindungi dari hujan dan panas, dari semua yang menyakitkan.
Karena pada akhirnya, apa yang kita bawa ketika kita pergi bukanlah jumlah uang yang kita simpan atau jabatan yang kita capai – tapi momen-momen yang kita rasakan dan kehadiran Tuhan yang selalu mengikuti ku. Dan momen-momen itu, tidak pernah bisa dibuat dengan “efisiensi” kayak bunga yang tidak bisa dipaksa mekar lebih cepat, karena keindahannya ada di proses menunggunya. Dia hanya muncul ketika kita berhenti, ketika kita mau merasakan, ketika kita mau membuka hati – kayak pintu yang hanya terbuka ketika kita mau mengetuk, dengan hati yang terluka tapi masih mau percaya karena Tuhan selalu ada di sisi.
Aku adalah seorang jurnalis muda yang memilih jalan sebagai rumah. Dan meskipun dunia terus mencoba menolak ku, aku akan terus jalan, karena itu adalah cara aku hidup dengan hati, bukan dengan mesin, sambil selalu merasakan yang Maha Kuasa yang memelukku dan mengarahkan langkahku kayak aliran sungai yang selalu menemukan jalan ke laut, meskipun harus melewati segala rintangan.
Editor : Aan