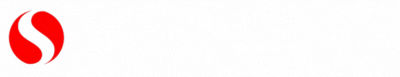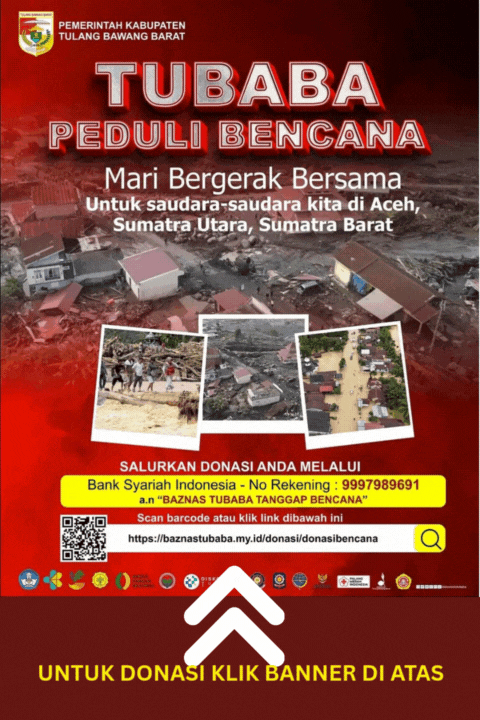Oleh : (Ahmad Basri : Ketua K3PP) | Minggu|22|10|2025.
Setiap konflik yang terjadi di tengah masyarakat pada dasarnya memiliki ruang penyelesaian. Tujuannya sederhana namun mendasar yakni menemukan jalan keluar agar tidak melahirkan kekerasan, anarkis atau dendam sosial yang merusak tatanan kemasyarakatan.
Konflik yang berkembang menjadi kekacauan biasanya bermula dari ketidakpuasan salah satu pihak terhadap pihak lainnya dimana ketika keadilan dianggap timpang dan suara masyarakat tak lagi didengar oleh negara atau korporasi.
Dalam konteks inilah pendekatan resolusi konflik menjadi sangat penting. Resolusi konflik tidak sekedar menekan gejolak sosial melainkan membangun jembatan komunikasi, membuka ruang mediasi dan menghadirkan keadilan substantif bagi semua pihak.
Ada dua jalur utama penyelesaian konflik. Jalur litigasi (jalur hukum formal) dan non-litigasi (jalur sosial, kultural, dan dialogis). Sayangnya keduanya sering kali tidak berjalan beriringan. Ketika hukum formal gagal menghadirkan keadilan, maka jalur sosial berbasis kearifan lokal kebudayaan menjadi harapan terakhir bagi masyarakat pencari keadilan.
Konflik antara Masyarakat Lima Keturunan Keluarga Besar Bandar Dewa dan PT. Huma Indah Mekar (HIM) di Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan salah satu contoh nyata dari kompleksitas konflik agraria di Lampung.
Sengketa tanah seluas 1.470 hektare yang berada di bawah sertifikat HGU No. 16 Tahun 1989 telah berlangsung selama bertahun – tahun dan berulang kali memasuki ruang litigasi. Namun jalur hukum formal tampaknya menemui jalan buntu. Ini yang dilalui saat ini.
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung memutuskan perkara tersebut dengan hasil “Niet Ontvankelijke Verklaard” (NO) yang berarti gugatan tidak dapat diterima.
Keputusan ini tentu menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan masyarakat adat khususnya Masyarakat Lima Keturunan Keluarga Besar Bandar Dew yang merasa tanah leluhur mereka dirampas secara sistematis sejak masa konsesi perusahaan.
Dari perspektif resolusi konflik kontemporer jalur non litigasi seperti mediasi, negosiasi, atau pendekatan berbasis kearifan lokal kebudayaan seharusnya menjadi alternatif strategis. Sayangnya pendekatan ini tampaknya belum ditempuh secara maksimal oleh kedua pihak.
Padahal di banyak daerah lain di Indonesia penyelesaian berbasis adat seringkali mampu mengembalikan harmoni sosial dengan cara yang lebih manusiawi dan bermartabat.
Di Kabupaten Tulang Bawang Barat sendiri, kita memiliki lembaga adat yang kuat, yakni Federasi Empat Marga Adat (Megou Pak) sebuah payung besar bagi empat marga utama (Buay Bulan, Buay Tegamoan, Buay Bulan Aji, dan Buay Umpu).
Lembaga adat ini secara struktural dan historis menjadi penopang nilai, norma, dan penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat Lampung Pepadun.
Saat ini Federasi Megou Pak dipimpin oleh Herman Arta, seorang tokoh adat yang memahami seluk – beluk tradisi dan dinamika sosial masyarakat Tulang Bawang Barat.
Menariknya bahwa Masyarakat Lima Keturunan Keluarga Besar Bandar Dewa merupakan bagian dari masyarakat adat Buay Tegamoan, maka secara moral dan kultural kebudayaan, Federasi Adat Megou Pak memiliki legitimasi sosial yang kuat untuk mengambil peran mediasi dalam menangani konflik.
Keberadaan lembaga adat bukan sekadar simbol budaya melainkan alat sosial rekonsiliasi yang dapat menjembatani kepentingan masyarakat adat dan pihak perusahaan bahkan dengan pemerintah daerah.
Dalam konteks resolusi konflik peran Megou Pak bisa meliputi: Menjadi mediator independen yang menjamin netralitas dan keterbukaan dialog. Mengumpulkan data dan kesaksian adat terkait sejarah penguasaan lahan sebelum adanya HGU. Menjadi penjaga legitimasi moral agar proses mediasi tidak dimonopoli oleh kepentingan politik atau ekonomi.
Peran Federasi Adat Megou Pak menawarkan penyelesaian berbasis rekonsiliasi budaya, seperti bentuk kompensasi, redistribusi, atau pengakuan hak kelola bersama yang berkeadilan bagi mereka yang berkonflik.
Keterlibatan Federasi lembaga adat Megou Pak dalam penyelesaian konflik agraria ini akan memperlihatkan bahwa adat dan hukum negara tidak harus saling meniadakan.
Namun dapat bekerja berdampingan untuk menegakkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18B UUD 1945 yang mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.
Pada akhirnya penyelesaian konflik pertanahan di Masyarakat Lima Keturunan Keluarga Besar Bandar Dewa bukan hanya soal siapa yang “berhak” secara hukum tetapi juga siapa yang berhak secara sejarah dan budaya.
Tanah bagi masyarakat adat bukan sekadar aset ekonomi melainkan ruang identitas spiritualitas dan kelangsungan hidup komunitasnya.
Ketika tanah diambil tanpa musyawarah maka yang hilang bukan hanya lahan tetapi juga martabat dan kepercayaan terhadap negara.
Karena itu Federasi Adat Megou Pak Tulang Bawang Barat seharusnya tampil sebagai penengah yang berdaulat secara moral, memfasilitasi dialog dan memastikan bahwa penyelesaian konflik tidak lagi berhenti di ruang pengadilan yang kaku.
Di tangan lembaga adat, rekonsiliasi kebudayaan bukan sekedar dokumen hukum melainkan pemulihan martabat dan keseimbangan sosial.
Jika lembaga adat berhasil memainkan peran itu maka tidak hanya menyelesaikan sengketa 1.470 hektare lahan tetapi juga mengembalikan kepercayaan masyarakat adat kepada keadilan itu sendiri.
Itulah mengapa Federasi Adat Megou Pak ini didirikan atau dibentuk sesungguhnya untuk bersuara bukan diam ketika melihat ketidak adilan